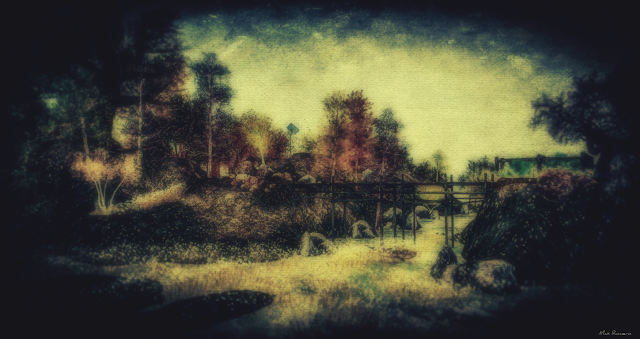Oleh: Samara
Angin berhembus menyibak fatamorgana di pagi hari. Bisikan
pohon rindu terdengar halus di telinga.
Kulalui jalan setapak, melewati kelas-kelas yang masih kosong. Langkahku
terhenti di depan TU MAN Gondanglegi yang sedang terbuka,
kulihat tumpukan kardus yang berisi majalah OASE. Hmmm, ini kan nanti
pembagian majalah. Kenapa majalah masih disini semua,
gumamku dalam hati. Pucuk dicinta ulam pun tiba, aku
melihat Aziza salah satu redaktur majalah.
“Za, mindahin
majalah yuk, biar ntar enak kalo pas pembagian majalah.”
“Boleh. Yakin nih
cuma berdua?”
“Yakiinnnnnn....”
Jawabku.
Kami mulai memindahkan majalah ke ruang jurnalis
yang tak jauh dari ruang TU, hanya terpisah oleh musalla
saja. Sedikit cerita, ruang jurnalis yang kami tempati tidak lebih luas dari
ruang kelas yang ada di sekolah kami.
Namun, ruangan inilah yang mampu memberikan warna-warni dalam kehidupanku,
khususnya di bidang jurnalisme.
Dalam ruangan ini saya belajar banyak hal, mulai dari cara bersosialisasi, cara
menyatukan perbedaan dan masih banyak lainnya. Aku terus menata majalah sesuai
dengan jumlah kelas yang ada. Seiring
berjalannya waktu semakin banyak yang berdatangan ke ruang jurnalis. Entah itu
redaktur yang datang untuk membantu atau perwakilan kelas yang datang untuk
mengambil majalah.
Biasanya mereka datang berdua atau bertiga, tapi
kali ini lain. Aku dikagetkan dengan segerombolan siswa-siswi yang berjalan
menghampiri ruang jurnalis. Sepertinya kalau dilihat dari badge yang berwarna kuning mereka
kelas XI sama denganku. Ah, rupanya benar
dugaanku, mereka personil XI Agama yang melakukan
pembelajaran di musalla. Memang
ketika pelajaran Ushul Fiqh mereka sering di musalla
untuk mempermudah proses pembelajaran. Anehnya mereka tidak segera masuk ke dalam musalla,
mungkin karena guru belum datang. Yah, beginilah memang anak SMA. Bukan segera
masuk ke musalla mereka malah memenuhi ruang
jurnalis.
“Ra, Ga
capek apa tiap hari mengurus majalah melulu?”
Iqbal, teman kelasku,
melontarkan pertanyaan ini padaku.
“Enggak lah,
kalau sudah hobi pasti
asyik.”
Ra ini ya, Ra itu
yaa. Dan masih banyak lagi obrolan yang kami lakukan di sana.
Selang beberapa menit, pak Lukman sudah datang
menuju musalla. Seketika itu juga ruangan jurnalis
serasa sepi dari pendemo.
“Ra....” Sapa beliau
padaku ketika melintasi ruang jurnalis saat hendak menuju musalla.
“Iya, Pak.”
Aku menjawab sambil tersenyum dan menganggukkan
kepala sebagai tanda rasa takzim kepada
beliau.
Setelah sapaan itu dan beliau berlalu menuju musalla,
aku merasakan sebuah perasaan yang tak nyaman. Bagaimana tidak, aku ada di ruang jurnalis tepat di teras,
sedangkan pelajaran kelasku sudah dimulai di dalam
musholla. Jelas terlihat aku sedang ada di luar.
Saat ini aku benar-benar memutar otak antara melanjutkan aktivitas
di ruang jurnalis atau meninggalkan ruangan dan menuju musalla
mengikuti pelajaran yang berlangsung. Ah, benar-benar pilihan yang sulit.
Sebenarnya kalau aku menuruti kemauanku yang malas ada di dalam ruangan kelas,
aku akan lebih memilih tetap tinggal di ruang jurnalis dan melakukan hobiku.
Yah, aku rasa ini lebih menyenangkan. Tapi tunggu, pikiranku berubah.
“Za, di kelasku pelajaran deh tuh kayaknya. Aku
kekelas ya.”
“Oke. Gak
masalah. Lagian ini sudah mau selesai kok.”
Aku mengambil tasku di ruang
jurnalis dan menuju musalla untuk mengikuti pelajaran Ushul
Fiqh. Aku ada di barisan paling belakang di sebelah
jendela. Menurut banyak
argumen, posisi ini memang posisi favorit bagi
semua kalangan. Aku menghayal memikirkan banyak hal hingga tak terasa aku tidur
selama pelajaran berlangsung. Setengah jam lebih aku tidur, aku terbangun
karena aku mendengar suara yang tak jauh dariku. Rupanya itu pak Lukman yang
sedang menelapon seseorang, entah siapa yang beliau telepon
hingga berdiri tepat di depanku.
“Ayo berangkat! Mana
temanmu, Wahidah
sama Ahmad?”
“Oh, iya,
Pak. Saya
cari dulu.”
Rasanya aku seperti sedang ada dalam dunia mimpi.
Aku berkhayal untuk keluar dari kelas beberapa
menit yang lalu dan akhirnya itupun terjadi dalam sekejap. Aku tahu
sekarang, Pak Lukman sedang menelepon
informan yang ada di Sitiarjo. Ketika beliau bilang berangkat aku sudah paham
bahwa yang beliau maksud adalah berangkat menuju desa Sitiarjo yang ada di
kecamatan Sumbermanjing untuk mengujungi salah satu informan penelitian yang
kita butuhkan. Saat ini aku dan kedua temanku, Wahidah dan Ahmad, memang sedang
mengikuti lomba Karya Tulis Ilmiah dalam pekan Kompetisi Sains Madrasah. Kami
bertiga dibimbing oleh bapak Lukman. Kami menghabiskan banyak waktu bersama di dalam dan di luar
jam sekolah untuk menyelesaikan penelitian ini. Bagi peneliti yang notabene masih SMA suasana hati yang
baik sangat menentukan bagi kelangsungan penelitian yang kami garap. Oleh sebab itu, tak jarang di sela-sela
proses penyelesaian kami berbagi cerita dan saling memberikan solusi.
Suasana kali ini berbeda.
Dengan mengendarai Elf sekolah kami bisa
mengajak beberapa orang yang dibutuhkan untuk membantu kelangsungan proses.
Biasanya mobil hanya terisi oleh kami berempat,
sekarang berisi 7 orang. Ada Arif teman kelasku yang kita mintai tolong untuk
mengambil gambar saat proses wawancara, ada Pak Wahyu
yang menyetir mobil Elf dan juga Aurel putri dari pak Wahyu
yang masih kecil. Berapapun isi mobil ini dan siapapun yang ikut aku tak
peduli, karena yang saya rasakan sekarang adalah kebahagiaan yang tak bisa kuluapkan
hanya sekadar dengan kata-kata. Sekarang kami menuju kantor Kepala Desa
Sitiarjo, tidak seperti biasanya Pak
Lukman hanya turun seorang diri dan membiarkan kami tetap di dalam mobil. Dari dalam kaca mobil aku
melihat Pak Lukman sedang berbincang-bincang
dengan kepala desa dan kemudian menuju Elf
kembali.
“Lurus terus Pak,
nanti kita berhenti di rumah yang ada
di sebelah lapangan.” Begitu
yang diucapkan Pak Lukman ketika masuk kembali ke dalam
mobil.
“Kita sekarang ke rumah salah satu tokoh kristen
yang ada di desa ini. Jangan lupa instrumen wawancaranya
ya.” Pak Lukman melanjutkan ucapannya.
Setelah mendengar ucapan beliau, sontak kami bertiga
saling bertatap muka. Tidak perlu ada kata-kata yang keluar dari mulut kami. Cukup
ekspresi ini yang mewakili sebuah pertanyaan, “Siapa
yang akan mulai wawancara?”
“Ayolah, Mad.
Ini bagianmu,”
pintaku kepada Ahmad
“Ah, mana bisa?! Gantian lah.
Kemarin aku
sudah, kalian kan belum.”
Lagi-lagi ini keputusan berat.
Memang benar yang Ahmad
bilang, sekarang giliranku dan Wahidah. Aku
menyayangkan jika harus Wahidah yang mengambil bagian ini karena dia cukup baik
dalam menulis hasil wawancara. Jika dia yang
ambil bagian ini otomatis aku yang akan menulis hasilnya.
“Okelah. Aku
yang wawancara sekarang.”
Kami turun dari mobil dan menuju rumah Pak
Woesgyanto namanya.
“Silakan masuk. Bapak
masih di belakang,” seorang
wanita separuh baya mempersilakan kami masuk.
Kami semua menunggu kedatangan beliau.
Sambil menunggu aku tak punya keinginan
untuk mematangkan apa yang akan aku tanyakan kepada beliau. Bukannya mengobrol
yang bermanfaat, kami malah mengobrol
ngalor-ngidul tidak
jelas.
“Sudah lama menunggu?” Dari
dalam terdengar suara seorang laki-laki. Orang
tersebut berbicara sembari menghampiri kami di ruang
tamu dan berjabat tangan.
Dalam benakku aku mengatakan bahwa beliau ini yang
namanya pak Wusgyanto, salah satu tokoh Kristen
desa Sitiarjo. Dari fisiknya dan caranya berbicara terlihat bahwa beliau tokoh
agama yang tegas dan disiplin.
“Ra, ini kayaknya mirip sama orang yang pernah kamu
ceritain itu deh.” Wahidah membuka pembicaraan denganku.
“Asli mirip banget dah. Aku
meerasa benar-benar
ada di masa lalu lagi dah.”
Wahidah tertawa cekikikan. “Siapkan
mental ya. Aku berdoa semoga
trauma di masa lalu enggak
terulang lagi.”
Memang ketika beliau datang rasanya seperti de javu alias sebuah peristiwa yang
seakan pernah terjadi di masa lalu dan sekarang terulang kembali. Aku memang
pernah menceritakan peristiwa di masa kecilku kepada Wahidah dan Ahmad. Di saat
masih kecil ada satu tetangga yang sangat aku takuti karena dia selalu
menakutiku ketika aku bersikap tidak baik. Peristiwa itu masih sangat membekas
dalam ingatanku. Dan sekarang aku harus berhadapan kembali dengan rasa takut
itu.
“Silakan dimulai.” Pak
Lukman langsung memberi perintah kepadaku ketika Pak
Lukman sudah selesai menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami.
Ah, ini ketiga kalinya aku harus berpikir
keras dalam satu hari ini. Kesalahanku yang tidak mempersiapkan instrumen
dengan jelas membuatku bingung, ditambah lagi Pak
Lukman yang terus menatapku memberikan sinyal perintah untuk segera dimulai.
Aku kebingungan, haruskah aku mulai menanyakan nama dalam wawancara ini secara
formal seperti yang biasa aku lihat dalam acara TV, tapi diawal tadi beliau
sudah menyebutkan nama. Aku bingung dengan diriku sendiri.
Tidak biasanya aku bersikap kaku begini.
Apa karena rasa takut yang berlebihan?
Belum sampai aku menanyakan satu hal tiba-tiba orang
di sekitarku menghilang satu persatu. Aku
melihat pak Lukman perlahan menghilang dari pandanganku, Wahidah yang semula ada
di sampingku kini entah kemana. Semuanya
menghilang, termasuk suguhan makanan dan minuman
yang ada di depanku. Aku sendiri di dalam rumah ini, penglihatanku terus
mencari-cari sesuatu yang dapat kutemukan di sekitarku.
Tapi nihil karena aku tak menemukan apa yang semula ada. Rasanya aku ingin
menangis, aku ingin menjerit sekuat mungkin agar mereka mendengarku dan
kembali. Apa yang sedang terjadi pada diriku? Aku
merasakan suhu tubuhku meningkat dan kepalaku terasa berat sekali. Selanjutnya
bobotku sangat ringan kurasakan bahkan lebih ringan dari angin sehingga tanpa
terasa aku melayang-melayang.
Tapi tunggu, aku dapat tersenyum sekarang. Aku
melihat lorong yang tak pernah aku lihat, lorong itu sangat indah sekali.
Lorong itu memancarkan sebuah cahaya terang. Aku semakin bingung, kenapa di rumah ini ada lorong rahasia yang penuh
dengan cahaya terang. Aku terus memandangi lorong itu semakin dekat semakin
indah sekali. Aku tersenyum dan terus melangkahkan kaki. Subhanallah,
gumamku dalam hati. Tidak hanya cahaya yang berkilauan, setelah aku mendekat
lorong itu semakin menampakkan keindahannya. Tanaman hijau dan bunga-bunga yang
harum semerbak mewangi.
“Ra! Ra!
Zahra!”
Jelas sekali aku mendengar ada yang memanggilku.
panggilan itu diulang-ulang. Aku terus mencari sumber suara itu. Sekarang
tubuhku seperti digoncang dengan kuat.
“Zahra sudah
sadar, zahra sudah bangun!” Teriak
Wahidah.
Suara Wahidah jelas sekali di telingaku.
Aku perlahan membuka mata dan aku melihat
pemandangan yang semula aku lihat. Ah, rupanya aku sedang jatuh pingsan. Tak
apalah, aku sudah merasakan lorong kebahagiaan.[]