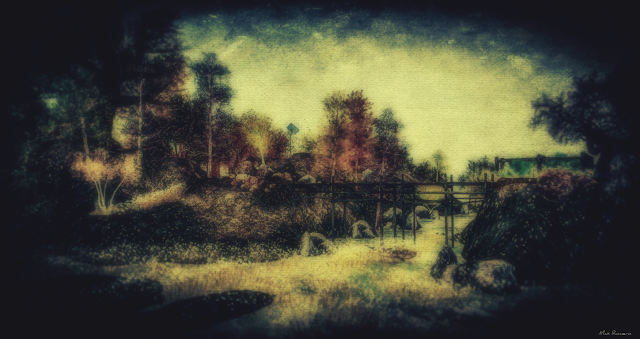Oleh: Halimah Garnasih
Menurut
KBBI, kata “keamanan” adala kata benda yang memiliki arti ‘keadaan aman’,
turunan dari kata sifat ‘aman’. Pada dasarnya kata ini tidak merujuk makna
‘lembaga’, ‘sebuah profesi’, atau ‘sosok; orang’. Namun, di beberapa Pesantren,
kata ini memiliki pergeseran makna. Di beberapa Pesantren tersebut, saat Anda
menyebut kata “keamanan”, maka konsep yang ada di benak pendengarnya akan
otomatis merujuk pada ‘Divisi’, ‘Profesi’, dan menyempit pada ‘sosok’. Umumnya,
kata ini akan mengalami penyempitan lebih dalam lagi pada makna “sosok yang
menjadi momok” warga Pesantrennya.
Menjadi
Keamanan Pesantren berarti menjadi santri yang paling ditakuti, dibenci, sering
dicurigai, sekaligus dicintai. Menjadi Keamanan Pesantren adalah hal yang
paling dijauhi, ditakuti, tapi diam-diam sekaligus diharapkan, diimpi-impikan,
dan dibangga-banggakan. Kursi jabatan Keamanan Pesantren (selanjutya ditulis
‘Keamanan’) adalah kursi yang sarat kontroversi, polemik, dan guncangan. Kenyataan
ini akhirnya menurun pada proses sosialnya dan tentu saja bergayut-kelindan
pada ‘sosoknya’.
Banyak
yang bilang, menjadi Keamanan itu banyak untungnya. Nah, tulisan ini hadir
untuk mengamini asumsi tersebut. Di bawah ini ada lima keuntungan Keamanan terkait
posisi yang bisa dipertaruhkannya berdasaran pengalaman kerjanya selama di
Pesantren.
Menjadi Jurnalis yang Handal
Tidak
tanggung-tanggung, Keamanan tidak hanya memiliki skill menjadi penulis dan
peneliti. Lebih dari itu, Keamanan bisa menjemput masa depannya yang penuh
tantangan dengan menjadi jurnalis yang handal!
Ini
berdasarkan pengalaman panjangnya dalam kerja Keamanan yang tidak mengenal
waktu dan tempat, kecuali hari liburan Pesantren tiba. Meski untuk kasus-kasus
tertentu kerja Keamanan tidak mengenal hari libur sih.
Keamanan
terbiasa mencari data aktivitas para santri dari absen-absen kegiatan pesantren
yang super banyak. Setelah mendapatkannya, data-data itu dikelompokkan, lalu
diteliti satu per satu. Dalam penelitian ini, Keamanan harus sangat teliti,
rinci, dan berhati-hati jangan sampai terlewat satu nama dan satu kegiatan pun!
Hal
ini karena berkaitan menentukan nasib seorang santri pada malam Jumat mendatang.
Apakah dia akan lolos masuk Kantor Keamanan yang menyeramkan, atau harus mendekam
dan menghabiskan malam Jumat nan sakral itu dengan menjawab setiap pertanyaan
yang diajukan kepadanya dengan tubuh gemetaran.
Data-data
yang telah diteliti dan dikumpulkan itu tadi harus melewati tahap selanjutnya,
yaitu verifikasi. Dan terakhir, Keamanan siap membuat laporan tertulis sebagai
bahan persidangan malam mengerikan bagi para kriminal.
Dan
sesungguhnya, dalam tahap akhir itu pun kerja Keamanan belum usai. Dia
berpindah mengumpulkan, meneliti, dan mengolah data yang tidak tertulis.
Data-data yang datang dari laporan beberapa pihak baik santri, pengasuh, maupun
masyarakat sekitar Pesantren. Juga hal-hal kriminal (dalam konteks Pesantren;
santri yang melanggar Tata Tertib Pesantren. Kriminal di Pesantren belum tentu
kriminal dalam konteks Hukum Negara) yang langsung ditemukan sendiri oleh
Keamanan.
Misalnya
ya, ini misalnya lo ya: Seorang Keamanan (santri) putri yang mendapatkan surat
titipan dari seorang santri putra untuk diberikan kepada santri putri. Kasus
ini terkadang yang membuat pertimbangan para santri putra dalam menghafal
wajah-wajah Keamanan putri.
Menjadi Intelijen Negara
Tidak
jamak diketahui memang, bahwa Keamanan diam-diam memiliki beberapa telik sandi.
Mereka datang dari para santri yang mustaqîm,
alias lurus dan sungguh tidak menyenangi para santri yang terang-terangan
melanggaran peraturan Pesantren. Mereka berkeyakinan, esensi nyantri adalah ngalap barokah. Dan esensi ini akan
menjadi berjarak dengan santri apabila mereka melanggar peraturan Pesantren.
Karena peraturan Pesantren memiliki turunan dari perintah dan larangan Kiai.
Keamanan
yang memiliki bekal menjadi intelijen adalah dia yang cerdas membaca fenomena.
Dia terlatih melihat, merekam, membaca dan menyikapi isu-isu Pesantren yang
hadir ke permukaan dengan cerdas. Karena bila tidak memiliki kemampuan
tersebut, alih-alih mendapatkan aktor-aktor yang bekerja di balik itu semua dan
menjaga kestabilan Pesantren, dia akan menjadi korban bentukan isu dan terkecoh
oleh para kriminal besar yang menjadi dalang dari semua kerusuhan. Ya, seperti
keadaan Jakarta saat ini. Aduh, padahal sudah ngempet-ngempet agar tidak menyentuh perbincangan ini!
Keamanan
juga terbiasa dituntut memiliki sudut pandang yang berbeda. Hal ini bukan untuk
memosisikan diri di titik oposisi biner dan berhadap-hadapan, tapi bagian dari
teknik melihat dengan holistik, juga menjangkau apa yang ada di sana. Sekaligus
apa yang ada di sini.
Sebenarnya
masih ada lagi. Tapi bagian ini harus unclassified,
bila tidak, bisa jadi bentuk-bentuk kriminalitas akan semakin kreatif. Bila hal
ini terjadi, Keamanan akan kelimpungan dan dituntut untuk lebih kreatif dalam
tekhnik-tekhnik kerja senyapnya. Jadi, energi Keamanan sebenarnya memang perlu
dimaksimalkan di titik ini, agar hasrat menyalurkan anarkisme (bila masih ada) sedikit
demi sedikit menjadi lunak. Tentu saja disertai mulai menerapkan hukuman yang lebih
manusiawi dan memiliki nilai edukasi. Sebuah kesadaran manusia-manusia
berperadaban.
Pendeknya,
Keamanan berpengalaman dan menerapkan dua kerja sekaligus, yaitu kerja FBI dan
kerja CIA!
Menjadi Polisi, Pengacara, dan Hakim
Kerja
Keamanan juga adalah kerja tiga profesi di atas sekaligus. Memanggil para saksi
untuk dimintai keterangan sudah bagaikan makanan sehari-hari bagi Keamanan. Keamanan
dituntut jeli menangkap keterangan para saksi baik keterangan verbal maupun non
verbal. Membaca keterangan dari bahasa tubuh dan dari garis-garis di raut muka
memang mendorong intelejensi Keamanan menjadi lebih dalam. Mana keterangan
verbal yang berbanding lurus dengan bahasa tubuh, dan mana keterangan verbal
yang bertolak dengan bahasa tubuh.
Di
sinilah Keamana juga sering dihadapkan dengan perilaku metafisis para saksi,
tersangka maupun korban. Sambil terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sarat
pancingan, semua indera harus aktif terjaga mengawal keadaan. Akan ada mulut
yang tidak henti-henti merapal berbagai amalan yang dipercaya mengecoh atau
membungkam Keamananan. Ada jari telunjuk yang bergerak-gerak memilin ujung kain
kerudung sambil fokus menatap Keamanan yang dituju agar kehilangan fokus pada
subjek, dan pola-pola metafisis lainnya oleh para saksi, tersangka, maupun
korban yang dihadirkan.
Dalam
menghadapi yang seperti ini, Keamanan juga terbiasa mengamalkan hizib dan
mengantongi rajah dan semacamnya sebagai bentuk advokasi metafisis. Ini
kelebihan yang barangkali tidak dimiliki Badan Keamanan Negara secara umumnya
baik Nasional apalagi Internasional (saat mendapat serangan metafisis, KPK
hanya menggunakan jasa, tidak melakukan sendiri). Di sinilah kemampuan
intelejensi, emosional, dan spiritualitas Keamanan sangat terasah. Hal ini
membentuk pribadi Keamanan sebagai sosok yang berkarakter, matang jiwa-raga.
Melewati
proses di atas, Keamanan akan memasuki fase pengolahan keterangan dan
memutuskan sebuah putusan. Di titik ini, ketegasan tanpa memandang bulu, dan
kebijaksanaan harus mampu dihadirkan dari jiwa seorang Keamanan. Menjadi sosok
yang bijak dengan mendasarkan keputusan sebuah putusan hanya dari simpul
putusan dan mengacu pada limitasi, berkas Tatib Pesantren. Semacam UUD nya Pesantren
lah ya.
Menjadi Pemimpin
Keamanan
telah terbiasa pandai mengorganisir waktu, juga antara yang pribadi dan yang
umum, bahkan di beberapa titik seringkali merelakan kepentingan pribadinya demi
mengutamakan kepentingan umum. Kerja Keamanan harus terus berlangsung sementara
kewajibannya sebagai santri dan peserta didik tetap menjadi tanggung jawabnya.
Ketika
santri masih nyenyak tidur, Keamanan harus bangun terlebih dulu demi memastikan
para santri telah bersiap melaksanakan salat jamaah saat pengasuh sebagai imam
subuh telah rawuh di Musalla. Saat
para santri telah mulai mengistirahatkan kedua matanya, Keamanan harus tidur
lebih akhir untuk mengontrol keadaan santri dan Pesantren di malam hari. Saat
santri nyaman belajar dan menghafal nazam di sela-sela kegiatan, Keamanan harus
cerdik nyambi hafalan di tengah
proses investigasinya. Bahkan, seringkali harus terjaga sampai menjelang subuh
karena kasus-kasus besar sedang ditangani.
Manajemen
dan skill organizing-nya sudah tidak perlu ditanyakan. Pengalamannya
melayani umat telah mengasah jiwa Keamanan sebagai jiwa yang rela berkorban.
Satu di antara hal esensial yang harus dimiliki seorang pemimpin! Dan yang terpenting, pelayanannya untuk
Pesantren menjadikannya santri yang dihujani barokah. Bersama barokah dari sang
Guru, kerja kepemimpinanya akan senantiasa dikawal oleh kerelaan dan doa-doa. Bertabur
barokah.
Menjadi Insan Kamil
Insan
kamil atau manusia sempurna adalah istilah sarkasme yang ditujukan untuk
Keamanan. Hal ini datang karena anggapan: benar atau salah Keamanan tetap
benar. Keamanan luput dari proses hukuman. Bersamaan dengan itu, hal sebaliknya
tertanam dalam kesadaran Keamanan: Salah atau benar, Keamanan selalu dipandang salah,
seperti tidak ada benarnya di mata santri. Bilamana keliru, maka hujatan dan
caci-maki akan datang bertubi-tubi. Bilamana berada pada jalur, bagaikan angin
lalu. Bilamana berhasil mencetak prestasi kerjanya, itu memang menjadi
sewajarnya.
Kenyataan
di atas sesungguhnya menjadi bagian dari faktor yang menghantarkan Keamanan
menjadi Insan Kamil (dalam arti yang sesungguhnya). Kontrol sosial yang dahsyat
terhadapnya, dapat menjadi rambu-rambu dalam menjalani aral hidupnya di
Pesantren. Jangankan meleot beneran,
hanya akan meleot saja, rambu-rambu
lekas berganti warna merah dan berbunyi nyaring sekali dan datang dari segala
arah.
Selain
menjadi kontrol sosial, kedua hal di atas akan membawa Keamanan pada titik
berkontemplasi tentang keberadaannya di dunia Pesantren. Lalu bergerak lebih
jauh, masuk pada spektrum yang lebih luas: kehidupan itu sendiri. Ia mulai
melakukan perjalanan pikir dan batin dan menemukan muaranya. Akhirnya ia
berjalan menemukan muara bukan karena kedua hal di atas. Bukan pula karena
Tatib Pesantren. Apalagi terjebak pada ketakutan normatif: Kabura Maqtan ‘Indallaahi.
Allaahu A’lam.
Malang, 25-26 November 2016
sumber gambar: somewhere @ pure dreams